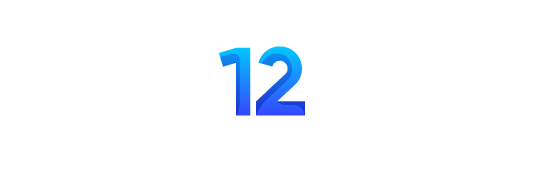Ditulis oleh Mahasiswa DIK Universitas Sahid, Edi Nurwahyu Julianto
Fenomena S-Line setelah muncul drama Korea terbaru garapan Ahn Joo Young berjudul S Line yang viral di media sosial. Kisah drama ini istilah S-Line bukan merujuk pada lekuk tubuh ideal, tapi menceritakan tentang garis merah misterius yang muncul di atas kepala orang-orang.
Garis merah itu menghubungkan penanda bahwa orang-orang yang pernah melakukan hubungan intim. Konsep ini semakin unik karena garis merah tersebut terhubung dengan pasangan yang pernah melakukan hubungan badan.
Sejak episode perdana, drama ini memantik rasa penasaran publik. Klip pendek, potongan adegan, hingga parodi drama ini membanjiri TikTok, Instagram Reels, dan Twitter/X. Dalam hitungan minggu, istilah S-Line menjelma menjadi simbol baru dalam diskusi seksualitas, baik di ranah hiburan maupun ruang publik digital.
Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Kepopuleran S-Line terjadi di tengah meningkatnya dominasi budaya pop Korea (Hallyu) di dunia global. Menurut Korea Foundation (2024), jumlah penonton konten drama Korea di seluruh dunia meningkat lebih dari 20% dibanding tahun sebelumnya, dengan 70% di antaranya menonton melalui platform streaming dan media sosial.
Karakteristik K-drama yang memadukan fantasi, kisah emosional, dan simbol unik menjadi alasan mengapa konten semacam ini cepat viral. Dalam kasus S Line, simbol “garis merah” menjadi daya tarik visual sekaligus metafora yang kuat, sehingga mudah diadaptasi menjadi tren digital.
Namun, fenomena ini juga mengundang perdebatan: apakah popularitas S-Line mencerminkan kemajuan pembicaraan publik tentang seksualitas, atau justru menciptakan bentuk baru dari stereotip dan stigma? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melihatnya melalui Teori Konstruksi Sosial atas Realitas dari Berger & Luckmann.
Teori ini menjelaskan bahwa apa yang kita anggap sebagai “realitas” adalah hasil kesepakatan sosial yang dibentuk melalui bahasa, interaksi, dan media. Konsep S-Line jelas merupakan realitas yang “diciptakan” oleh media hiburan, lalu diobjektifikasi dan diinternalisasi oleh publik melalui interaksi di media sosial.
Dalam konteks fenomena ini, eksternalisasi seorang penulis naskah dan sutradara yang memperkenalkan ide garis merah sebagai metafora hubungan intim. Melalui drama televisi, ide tersebut diekspresikan secara visual, lengkap dengan narasi emosional yang membuatnya terasa masuk akal di dunia cerita.
“Objektivasi terjadi ketika jutaan penonton menerima ide ini sebagai bagian dari pengalaman menonton mereka, bahkan memperluasnya ke ruang digital melalui meme, video pendek, atau filter “garis merah” di aplikasi media sosial,” kata dia
Akhirnya, internalisasi terjadi ketika masyarakat mulai menggunakan istilah S-Line dalam percakapan sehari-hari, baik dengan konteks humor maupun sebagai simbol penilaian terhadap hubungan seseorang.
Media sosial berperan besar dalam mempercepat proses konstruksi ini. Algoritma TikTok dan Instagram dirancang untuk mengangkat konten yang memicu keterlibatan emosional. Tren S-Line memenuhi semua syarat itu: visual yang mencolok, narasi kontroversial, serta potensi humor yang luas. Menurut laporan DataReportal (2025), 70% konten yang trending di TikTok bulan Mei–Juni 2025 berasal dari adaptasi budaya populer Asia, dan drama Korea menduduki peringkat teratas.
Tren ini membuktikan bahwa media sosial bukan hanya kanal distribusi hiburan, tetapi juga ruang di mana realitas sosial—termasuk pandangan tentang seksualitas—dibentuk dan dinegosiasikan.
Bahasa dan simbol menjadi kunci dalam fenomena ini. Garis merah di atas kepala bukan sekadar efek visual, tetapi sebuah simbol komunikasi yang mudah diinterpretasikan: semakin banyak garis, semakin banyak pengalaman intim seseorang. Di media sosial, bahasa visual seperti ini dengan cepat menjadi “kode sosial” baru.
Bahkan banyak kreator konten menggunakan efek garis merah untuk bercanda tentang kehidupan percintaan mereka, atau bahan sindiran terhadap selebritas dan figur publik. Dalam pandangan Berger & Luckmann, ini adalah bentuk institusionalisasi makna, di mana simbol fiksi dari sebuah drama berubah menjadi bagian dari percakapan publik yang nyata.
“Dampak fenomena ini cukup kompleks. Dari sisi positif, S-Line membuka ruang diskusi tentang seksualitas yang selama ini dianggap tabu, terutama di masyarakat Asia yang cenderung konservatif,” ungkapnya.
Fenomena ini memungkinkan orang untuk berbicara tentang hubungan intim dengan cara yang ringan, kreatif, dan humoris. Bahkan pengguna media sosial, khususnya generasi Z, melihat tren ini sebagai bagian dari ekspresi kebebasan berekspresi dan keterbukaan dalam membicarakan hal-hal yang dulunya dianggap memalukan.
Di sisi lain, ada juga dampak negatif. S-Line bisa menjadi alat untuk menghakimi atau merendahkan orang lain. Misalnya, komentar-komentar bernada “slut-shaming” muncul di kolom komentar video yang menggunakan filter ini, seakan-akan jumlah garis merah menjadi indikator moralitas seseorang.
Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial tentang seksualitas yang muncul dari budaya pop bisa memiliki efek samping berupa normalisasi stigma baru.
Beberapa pakar komunikasi digital memberikan pandangan kritis terhadap tren ini. Peneliti media di Yonsei University Prof. Kim Yoon-seo menilai bahwa fenomena seperti S-Line menunjukkan bagaimana media hiburan modern “mengkomodifikasi” seksualitas menjadi tontonan visual.
“Jadi apa yang seharusnya menjadi ruang privat kini diangkat menjadi tontonan publik. Media sosial mempercepat proses ini, mengubah sesuatu yang tabu menjadi hiburan massal,” ujarnya (Kim, 2024).
Pakar komunikasi digital dari Microsoft Reserch, Dr. Nancy Baym menekankan bahwa tren semacam ini adalah bagian dari attention economy, di mana konten yang memicu rasa ingin tahu dan kontroversi akan mendapatkan visibilitas tertinggi.
“Dalam ekonomi perhatian seperti ini, isu yang sensitif seperti seksualitas mudah sekali dipermainkan sebagai komoditas viral,” ungkap dia.
Studi Seoul National University (2025) menemukan bahwa lebih dari 40% pengguna TikTok di Korea Selatan mengunggah atau mengonsumsi konten terkait drama S Line, dan 55% di antaranya mengaku bahwa tren ini mempengaruhi cara mereka membicarakan topik seksualitas.
Data ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial yang dihasilkan media hiburan tidak hanya sekadar tren sesaat, tetapi juga memiliki dampak pada pola komunikasi publik.
Pro-kontra mengenai fenomena S-Line semakin mengemuka ketika influencer dan selebritas ikut mempopulerkannya. Sebagian pihak melihat hal ini sebagai bentuk kreativitas budaya pop, sementara sebagian lainnya menganggapnya merusak norma budaya.
Lembaga sensor di beberapa negara Asia Tenggara bahkan sudah mulai mempertimbangkan apakah konten S-Line di media sosial melanggar norma kesusilaan. Namun, di era digital yang serba terbuka, pengaturan semacam ini sering kali tidak efektif, karena tren viral sangat sulit dibendung.
Melihat fenomena ini dari perspektif komunikasi, kita bisa bertanya: Apakah viralitas S-Line adalah bentuk kebebasan budaya, atau tanda bahwa privasi seksual semakin tereduksi menjadi komoditas visual?
Teori konstruksi sosial Berger & Luckmann mengingatkan kita bahwa makna yang kita terima tidak pernah netral; ia selalu lahir dari proses sosial yang penuh kepentingan, baik ekonomi, budaya, maupun politik.
Dalam kasus S-Line, kepentingan industri hiburan jelas terlihat. Drama ini tidak hanya meraih rating tinggi, tetapi juga menghasilkan gelombang promosi tak langsung melalui ribuan video viral.
Brand kosmetik, fashion, hingga aplikasi editing foto turut memanfaatkan tren ini untuk memasarkan produk mereka. Seksualitas, dalam hal ini, tidak hanya menjadi tema hiburan tetapi juga menjadi komoditas ekonomi digital.
“Untuk itu, penting bagi publik memiliki literasi media yang memadai. Kita perlu memahami bahwa fenomena seperti S-Line hanyalah representasi fiksi yang telah dikemas sedemikian rupa agar menarik perhatian,” ujarnya.
Menerima tren ini secara mentah-mentah tanpa kritik bisa berbahaya, karena kita secara tidak sadar ikut memperkuat konstruksi sosial yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri.
Di sisi lain, kita juga bisa memanfaatkan fenomena ini untuk memulai dialog yang lebih sehat tentang seksualitas, privasi, dan etika komunikasi digital. Alih-alih hanya menertawakan atau mengejek, kita bisa menggunakannya sebagai sarana edukasi: bagaimana cara menghargai privasi orang lain di era di mana kehidupan pribadi sering dijadikan konsumsi publik?
Penutupnya, fenomena S-Line adalah bukti nyata bahwa media sosial adalah medan komunikasi yang dinamis, di mana simbol dari dunia fiksi bisa dengan cepat menjadi realitas sosial. Teori konstruksi sosial membantu kita memahami bahwa tren semacam ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga alat pembentuk makna sosial yang memengaruhi cara kita memandang seksualitas, moralitas, dan relasi antarindividu.
Media sosial bukan hanya menyalurkan tren ini, tetapi juga menguatkannya melalui algoritma yang mendorong konten paling provokatif dan visual untuk muncul di beranda pengguna.
“Sudah saatnya kita, sebagai audiens digital, bersikap kritis. Kita harus mampu membedakan mana yang sekadar hiburan, mana yang bisa membentuk persepsi publik secara berbahaya. S-Line memang sekadar fiksi, tetapi resonansi sosialnya sangat nyata,” pungkasnya.